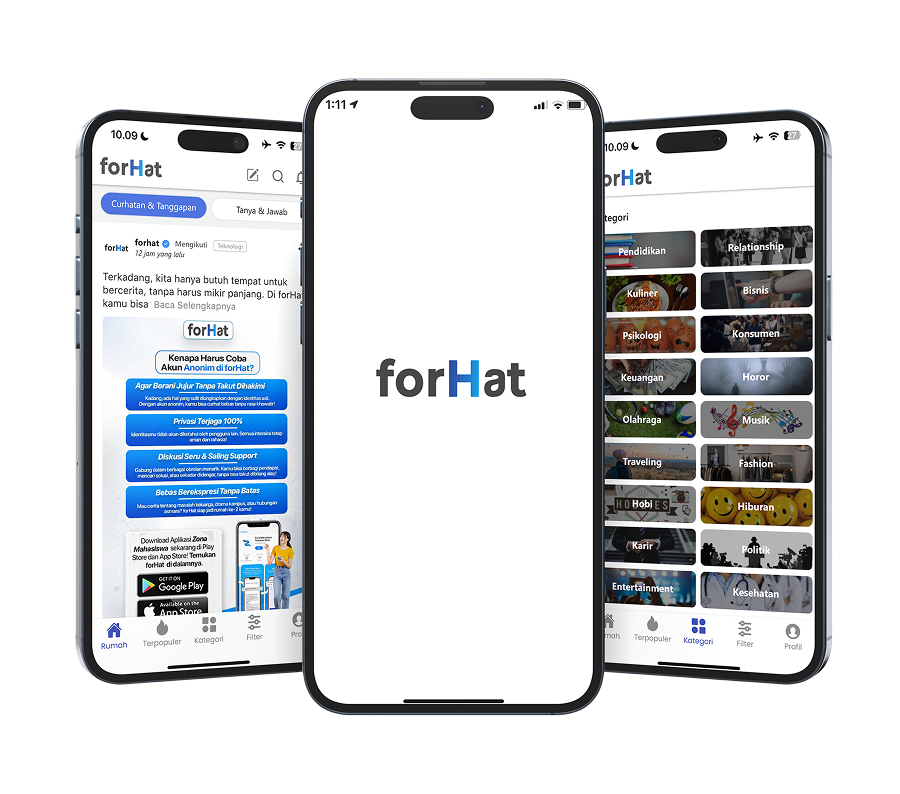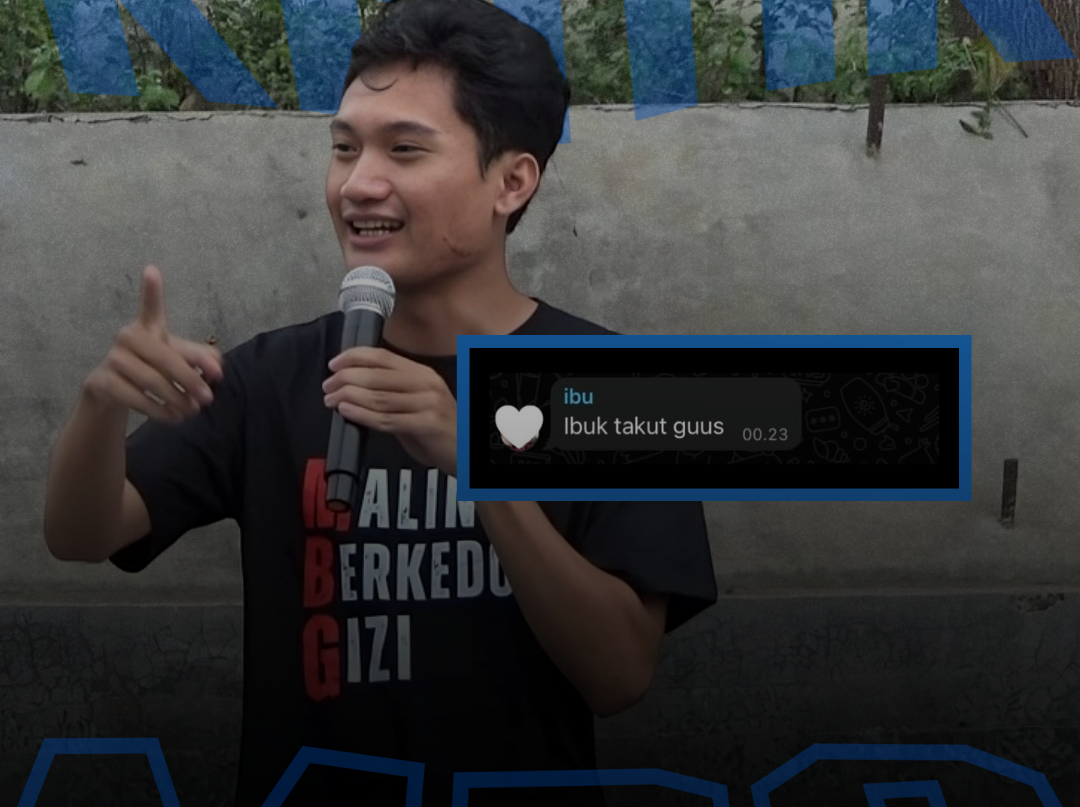Zona Mahasiswa - Kisah mahasiswa S3 yang viral karena tertawa di koridor kampus bukan karena bahagia, melainkan karena menertawakan nasibnya sendiri, adalah gambaran jujur dari realitas pendidikan tinggi hari ini. Mahasiswa S3 telah bertransformasi dari 'calon doktor' yang agung menjadi 'buruh pengetahuan' yang terjebak dalam mesin kapitalisme akademik.
Tulisan ini, yang terasa seperti curahan hati kolektif, mengungkap deretan absurditas, alienasi, dan tekanan struktural yang dialami oleh kelas menengah akademik mereka yang modal pendidikannya tinggi, tetapi kondisi materialnya seringkali mepet.
S3: Dari Mitos ke Realitas Proyek Output
Dilansir dari Modjok.co Mitos mengatakan S3 adalah perjalanan intelektual yang megah; realitasnya, S3 adalah proyek panjang dengan spesifikasi yang terus berubah dan auditor yang tanpa ampun.
Negosiasi Tanpa Akhir: Mahasiswa S3 kini hidup dalam negosiasi yang melelahkan: dengan supervisor (nabi kecil yang menafsirkan metodologi), dengan reviewer (malaikat pencatat dosa konseptual), dan yang paling sulit, dengan diri sendiri yang ingin menyerah tapi terhalang gengsi.
Kondisi Kelas Menengah Akademik: Label elit intelektual tak sejalan dengan kondisi material. Mahasiswa S3 seringkali terjepit: pendapatan tidak stabil, biaya hidup tinggi, dan target publikasi (Q1-Q4) terus menumpuk. Ironisnya, di grup keluarga dipanggil "calon doktor" dengan bangga, sementara di rekening bank disebut "saldo tidak mencukupi."
Akademia sebagai Mesin Kapitalisme Pengetahuan
Kampus, yang dulu diromantisasi sebagai taman pengetahuan, kini beroperasi layaknya korporasi. Pengetahuan telah menjadi komoditas yang diukur dan diproduksi massal.
Fetisisme Komoditas Akademik: Tugas utama mahasiswa S3 adalah memasok pabrik jurnal dengan artikel yang memenuhi standar: kebaruan, rapi, dan patuh format. Idealismu boleh tinggal, asalkan template rapi.
Pengetahuan diukur bukan dari impact sosialnya, melainkan dari metrik akademik seperti indeks sitasi, H-index, dan Sinta/Scopus. Kritik ala Marx terasa relevan: Relasi produksi pengetahuan ini menghasilkan fetisisme komoditas akademik—angka, metrik, dan indeks dianggap sebagai kebenaran, mengalahkan realitas sosial yang seharusnya diubah.
Hierarki Publikasi yang Kejam:
- Keren: Q1
- Lumayan: Q2
- Masih bisa: Q3
- Mohon introspeksi: Q4
Nasib riset ditentukan oleh Reviewer 2, manajer mutu yang bisa menolak produk hanya karena cacat ukuran satu milimeter, atau meminta "kerangka teori baru yang menjembatani semua perspektif yang tampak kontradiktif" – sebuah permintaan yang nyaris mustahil tanpa revolusi paradigma.
Alienasi Akademik: Ketika Ilmu Kehilangan Makna Sosial
Teori alienasi Marx (keterasingan manusia dari kerja, produk, sesama, dan dirinya sendiri) menjelma dalam versi akademik:
- Terasing dari Diri Sendiri: Menulis bukan karena ingin, tapi karena Key Performance Indicator (KPI).
- Terasing dari Produk: Meneliti masalah sosial, tetapi tersandera template dan style guide. Fokus bergeser dari merawat realitas sosial menjadi merawat estetika metodologis.
Alienasi mencapai puncaknya saat riset "sukses." Artikel terbit, sitasi naik, tapi apakah lapangan berubah? Apakah orang yang diwawancarai hidupnya membaik? Seringkali tidak. Ilmu berhenti di paywall; pengetahuan menjadi arsitektur indah yang jarang dihuni oleh masyarakat.
Ritus Harian Buruh Pengetahuan S3
Mahasiswa S3 adalah spesies lucu yang hidup di antara gengsi dan genset. Rutinitas harian mereka adalah maraton tanpa henti:
- Pagi: Briefing asisten riset.
- Siang: Mengurus komite etik, mengajar demi tambahan.
- Sore: Diskusi teori.
- Malam: Coding regresi, merevisi tabel, membalas email supervisor di zona waktu yang berbeda.
Untuk tetap waras, mereka melakukan ritus perlawanan kecil: jogging sambil menghafal defense (rehearse defense), menonton video statistik YouTube yang menyelamatkan jiwa, atau—yang paling puitis—menangis elegan di toilet perpustakaan karena akustiknya bagus.
Mereka tetap bertahan di sistem karena pasar kerja menilai mereka dengan logika yang sama: angka dan sertifikat. Menolak sistem, sayangnya, adalah bunuh diri karier.
Perlawanan Kecil yang Manusiawi
Perlawanan yang paling mungkin dan masuk akal di akademia bukanlah manifes besar, tetapi tindakan kecil yang konsisten dan merawat sesama:
- Membuka Akses: Mengunggah preprint, berbagi dataset yang aman, dan membuat ringkasan riset dalam bahasa publik agar ilmu tidak berhenti di paywall.
- Mengajar dengan Empati: Membantu mahasiswa berpikir kritis, bukan sekadar mengejar nilai.
- Kolaborasi Egaliter: Memberikan kredit yang layak kepada asisten riset dan menuliskan nama penulis sesuai kontribusi, bukan hierarki.
- Merawat Komunitas: Membangun peer support dan ruang diskusi berbiaya rendah untuk menjaga kesehatan mental.
Perlawanan ini tidak akan tercatat di H-index, tetapi akan tercatat dalam ingatan orang-orang yang kelak membuat akademia menjadi sedikit lebih manusiawi.
Disertasi S3 bukanlah mahakarya yang harus sempurna, melainkan jejak perjalanan dan bukti bahwa kita pernah berusaha keras memahami dunia secara serius.
Maka, jika kamu melihat mahasiswa S3 tertawa di koridor, pahami bahwa itu adalah tawa pilu menertawakan sistem, bukan karena bahagia. Ia adalah buruh pengetahuan yang menertawakan dunia sebelum dunia menertawakannya lebih dulu. Ia bertahan dalam bayang-bayang kapitalisme akademik, tetapi hatinya tetap berpihak pada mereka yang tak punya akses ke pengetahuan. Dan karena itu, ilmu yang dia tulis tidak akan pernah berhenti di paywall.
Baca juga: Mahasiswa Yatim Piatu Tewas Dikeroyok saat Numpang Tidur di Masjid Agung Sibolga
Komentar
0